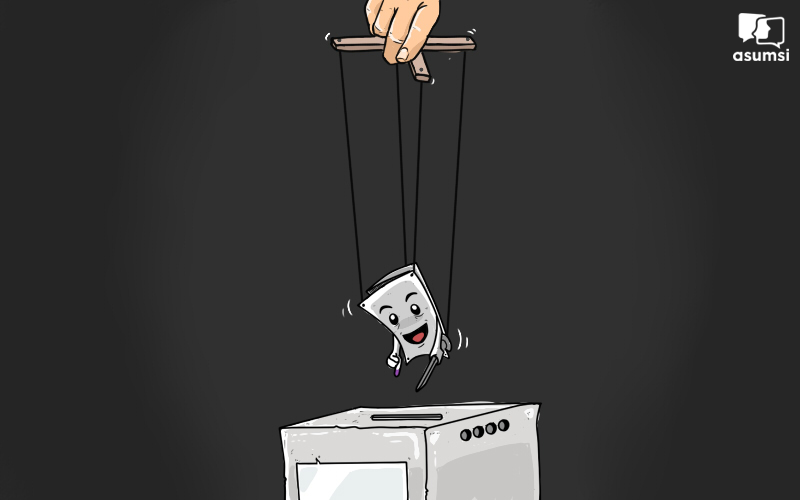Bermasalahnya Sistem Kolektif Kolegial KPU RI
Penangkapan dan penetapan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI 2019-2024 menimbulkan dampak buruk. KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai memiliki celah, terlebih sistem kolektif kolegial di internalnya yang tak berjalan baik.
Wahyu Setiawan diduga menerima suap dengan menjanjikan politisi PDI Perjuangan (PDI-P), Harun Masiku agar bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Wakil Ketua KPK, Lily Pintauli Siregar, menyebut Wahyu diduga meminta uang hingga Rp900 juta ke Harun.
Kondisi ini dinilai sangat miris apalagi kalau melihat kondisi masyarakat yang terpolarisasi menjadi dua kubu selama berlangsungnya Pemilu 2019 lalu. Situasi politik saat itu betul-betul tak mengenakkan, belum lagi banyaknya korban jiwa berjatuhan dari kalangan petugas pemilu demi penyelenggaraan pesta demokrasi yang damai dan adil.
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengaku kecewa dan marah terkait penangkapan Wahyu Setiawan. Ia berharap masalah ini bisa segera diselesaikan, karena ancamannya atau daya rusaknya bisa cukup serius terhadap KPU. Apalagi, KPU juga sedang mempersiapkan perhelatan Pilkada Serentak 2020.
“KPK juga harus segera menuntaskan kasus ini. KPU harus kerja bareng supaya kasus ini bisa cepat selesai. Sementara KPU perlu menguatkan sistem kontrol mereka, terhadap pemberantasan korupsi, kode etiknya, dan seterusnya,” kata Hadar kepada awak media usai acara Catatan Awal Tahun Perludem 2019-2020 di D Hotel, Jakarta, Jumat (10/01/20).
KPU Perlu Membangun Whistle-Blowers System
Hadar berharap ada perbaikan di internal KPU. Ia pun sepakat dengan usulan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mendorong KPU untuk bekerja sama dengan KPK membangun whistle-blowers system (WBS). Langkah itu perlu diambil untuk mencegah terjadinya kembali praktik korupsi di internal KPU.
“Jadi memang KPU harus segera melakukan sejumlah langkah perbaikan internal agar praktik yang sama tidak terulang kembali,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (10/01).
Dengan kerjasama membangun WBS tersebut, maka akan memungkinkan bagi anggota KPU untuk mengadukan atau melaporkan ke KPK terkait adanya dugaan korupsi yang akan atau sudah terjadi di lingkungan KPU. Yang jelas, keberadaan sistem WBS itu akan memudahkan KPU dalam melakukan pengawasan, tak hanya di tataran KPU Pusat saja, tapi juga di jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Komisioner KPU dan Politisi PDIP Jadi Tersangka Suap
“Whistle-Blowers System seperti yang diusulkan kawan-kawan ICW, artinya di dalam KPU itu harus dibangun sistem yang memudahkan, yang ada mekanisme jelasnya. Bawahan atau siapapun di internal KPU itu bisa saja bercerita kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terlihat. Sistem itulah yang belum terbangun selama ini di KPU,” ujarnya.
Terkait hal ini, KPK memang sudah menerapkan WBS dalam menjalankan tugasnya. Siapa saja bisa melaporkan dugaan kasus korupsi kepada KPK, di mana komisi anti-rasuah itu akan menjamin identitas si pelapor, sehingga privasi dan keamanan pribadi pun terjaga.
Perkuat Lagi Sistem Kolektif Kolegial Internal
Sorotan paling luas lainnya dalam kasus suap Wahyu Setiawan ini adalah soal mekanisme atau langkah internal KPU dalam mengambil keputusan strategis. Bagaimana Wahyu bisa tergerak sendiri menyanggupi untuk membantu Harun agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI terpilih 2019-2024? Apakah sistem kolektif kolegial di KPU tidak bekerja dengan baik?
“KPU harus menjalankan sistem kolektif kolegial itu dengan baik. Jadi bukan hanya dalam mengambil keputusan finalnya, sementara tugas-tugas yang lainnya kerja sendiri-sendiri misalnya, yang satu tiba-tiba nggak ada, kerjanya di mana. Komunikasi harus lancar dan kerja harus bareng,” kata Hadar.
Menurut Hadar, semua komisioner KPU tanpa terkecuali harus terbuka dan transparan terkait aktivitas yang terjadi selama masa tugasnya. “Kasih tau saja misalnya hari ini ada pimpinan partai politik yang menelepon, atau ada caleg datang menghadap misalnya, sebutkan apa keperluannya. Itu semua harus dikomunikasikan ke sesama komisionernya, semua harus tau, dan terbuka.”

Jadi, lanjut Hadar, sistem tersebut harus dibangun karena itu yang dinamakan sistem kolektif kolegial yang utuh dan penuh. Jadi bukan hanya dimaknai dengan pengambilan keputusan finalnya saja yang kolektif kolegial. Sistem kolektif kolegial itu sendiri merupakan sistem dalam suatu organisasi di mana untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan adanya suatu koordinasi antara satu pimpinan dengan pimpinan lainnya.
Selain itu, kepemimpinan kolektif kolegial merupakan istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan
Dalam sistem kolektif kolegial, masing-masing pimpinan itu memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam sebuah lembaga. Pengambilan keputusannya pun dilakukan melalui musyawarah atau bersama-sama (kolektif). sistem kolektif kolegial diikat oleh tujuan yang sama.
Nah, ikatan dan interaksi dalam kepemimpinan kolektif kolegial adalah ikatan untuk mewujudkan visi misi lembaga yang telah disepakati. Jadi dalam konteks KPU, semestinya tak ada keputusan-keputusan yang diambil sepihak oleh komisioner tertentu dalam kasus tertentu, semua keputusan harus diputuskan secara bersama-sama, di mana semua pimpinan bertanggung jawab.
“Sebetulnya KPU kokoh juga, jadi mereka kerja dengan aturan bahwa ini sudah putusan pleno dan seterusnya, sudah sesuai aturan. Nah itu sudah terbukti, bagus. Tapi juga yang harus kita ingatkan dan yang harus dibenahi, ada sisi lain, ini bukan sisi seolah penyelenggaraannya buruk ya, tapi ada sisi partai politik yang merusak,” kata mantan Komisioner KPU tersebut.
Baca Juga: Bagaimana KPK Menggelar OTT Tanpa Izin Dewan Pengawas?
Menurut Hadar, manuver partai politik secara sistematik seperti mau merusak. Dalam kasus Wahyu, terlihat bahwa pergerakan partai seperti semaunya saja. Misalnya saja setelah pemungutan suara selesai, peraturan perundang-undangan jelas mengatakan bahwa yang terpilih itu adalah yang memiliki suara terbanyak.
Mau dalam kondisi ada caleg yang meninggal atau ada yang mengundurkan diri, tentu yang harus diambil dan dipilih adalah sosok yang memiliki suara terbanyak berikutnya. Dalam kasus ini, caleg PDIP Riezky Aprilia memperoleh suara terbanyak, sehingga ditetapkan sebagai anggota DPR RI terpilih menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.
Menurut Hadar, partai politik nggak boleh otoriter, oligarki, dan mestinya harus bisa menghormati mekanisme yang ada. Ia juga mengingatkan bahwa dalam kasus seperti ini, peradilan tak boleh ikut terlalu jauh dalam proses yang ada.
“Tapi kelihatan kan dari proses peradilan yang begitu cepat, padahal di UU sudah jelas bagaimana menentukan caleg yang terpilih dan dinyatakan menang, lalu ada ide-ide bahwa ini diserahkan ke partai politik, bahwa suara orang meninggal itu diserahkan atau ditentukan sendiri oleh partai politik.”
“Kan itu semua menyimpang. Jadi ini sisi lain yang harus dibenahi dan KPK harus kejar itu. Ini jelas ada persoalan partai politik yang bermasalah, bukan hanya soal penyelenggara pemilunya saja. Jadi ini harus dibongkar.”