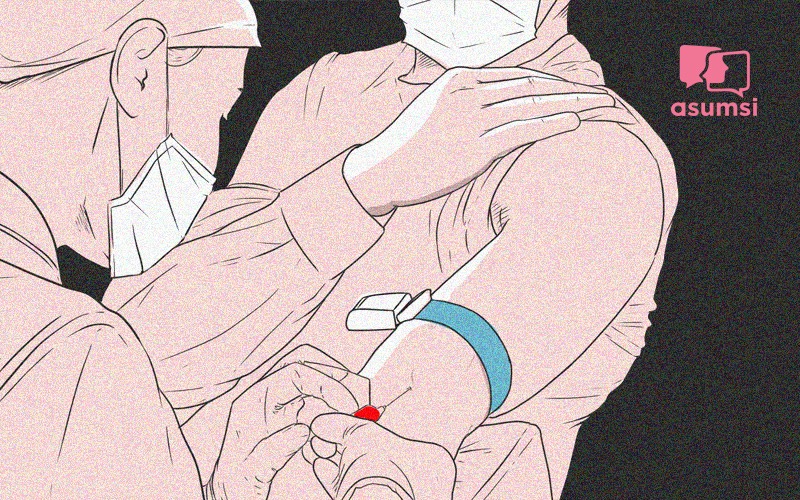Saya Diisolasi 14 Hari Karena COVID-19, Beginilah Pengalaman Saya
Kemarin (12/3), saya diimbau untuk mengisolasi diri selama 14 hari akibat pandemi virus COVID-19. Muasalnya sederhana: saya merasa tidak enak badan. Beberapa pekan terakhir, saya kerap merasa letih dan meriang disertai batuk pilek. Obat flu biasa gagal menuntaskannya. Ketika kemarin subuh saya terbangun dalam keadaan sesak napas, saya mengambil inisiatif menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.
Pemerintah menyediakan hotline COVID-19 yang dapat dihubungi kapan saja pada nomor telepon 119 ext. 9. Setelah menelepon, saya diminta menjelaskan gejala yang saya alami secara rinci. Petugas 119 menyampaikan pada saya bahwa gejala COVID-19 memang amat mirip dengan flu biasa yang boleh jadi disebabkan perubahan cuaca ekstrem belakangan ini. Namun, apakah saya berkontak dengan orang yang positif COVID-19 atau habis bepergian dari negara positif COVID-19?
Dari sini keseruan dimulai. Nadanya berubah saat tahu gedung tempat saya berkantor banyak dihuni perusahaan multinasional yang pekerjanya kerap bepergian ke luar negeri. Selain itu, psikolog saya baru pulang dari perjalanan ke Eropa. Meski saya tidak pernah kontak langsung dengan orang yang positif terkena virus COVID-19, supaya aman saya diminta petugas hotline untuk memeriksakan diri ke RS terdekat.
Sejam kemudian, saya periksa di RS Pelni, Jakarta Barat. Sedikit tips: bersiaplah untuk melihat air muka semua orang berubah saat Anda bilang ingin periksa diri untuk gejala COVID-19. Semua orang bakal terlihat tiga kali lipat lebih ramah sekaligus waspada. Abaikan.
Setelah suhu badan serta tekanan darah saya diperiksa, saya dikirim ke posko khusus COVID-19 yang telah mereka persiapkan. Dalam posko tersebut, saya dijelaskan prosedur berikutnya. Saya akan melakukan tes darah serta rontgen terlebih dahulu, dan hasil tes tersebut akan dibagi ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Apabila pihak Dinas Kesehatan mendapati sesuatu yang abnormal dalam hasil tes saya, maka saya akan mengikuti penanganan lebih lanjut.
Menariknya, jelang tes darah dan rontgen saya diminta berdiam di ruang isolasi, termasuk saat menunggu hasil tes keluar. Saya tidak diperbolehkan keluar ruangan sama sekali. Tes darah dan rontgen pun dilakukan di ruangan dengan alat yang mereka bawa dari tempat lain. Setelah menunggu beberapa jam, vonis saya turun.
Saya mengalami infeksi paru-paru. Boleh jadi disebabkan virus biasa, tak mesti COVID-19 yang sedang nge-hits itu. Dampaknya ganda: bisa saja saya diam-diam membawa virus dan infeksi ini adalah gejalanya, atau infeksi ini bisa bikin saya jauh lebih rentan terhadap virus itu di luar sana. Yang jelas, sebagai bentuk pengamanan, saya diminta untuk mengisolir diri selama 14 hari di rumah.
Satu hal bikin saya heran: vonis tersebut turun, padahal saya tak pernah diminta melakukan tes khusus COVID-19. Untuk menentukan apakah saya terinfeksi virus tersebut, semestinya saya diminta melakukan swab test. Mukosa dari pangkal hidung saya akan diambil, dikirimkan ke laboratorium, kemudian diperiksa. Umumnya, hasil tes turun dalam 24-72 jam.
Persoalannya, tak semua laboratorium mampu mengolah tes COVID-19. Peralatan ujinya mesti berstandar WHO, sebab bila tidak, ketepatannya layak diragukan. Di Indonesia, kita cuma punya satu fasilitas yang mampu mengolah hasil tes COVID-19: laboratorium Balitbangkes di Kementerian Kesehatan Indonesia.
Tak heran bila Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencurigai jumlah kasus saat ini COVID-19 hanyalah gunung es. Singkatnya, sebetulnya ada banyak kasus yang terjadi di luar sana. Kita tidak tahu, sebab satu-satunya laboratorium yang mampu menentukan mana yang positif dan negatif COVID-19 sedang kewalahan.
Kita tidak sendirian. Di Amerika Serikat, birokrasi yang ruwet, minimnya kapasitas laboratorium, hingga respon lamban pemerintah juga berujung pada fenomena gunung es serupa. Pandemi macam COVID-19 bukan hanya soal menjaga imunitas atau ramai-ramai menenggak susu kambing liar. Ia berkelindan erat dengan kemampuan suatu pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan masyarakat yang baik.
Ketika saya menanyakan mengapa saya diminta mengisolir diri meski tak pernah dites COVID-19, jawabannya ngeri-ngeri sedap. Saya tidak pernah kontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, dan gejala yang saya tunjukkan sejauh ini terbilang ringan. Suhu tubuh saya wajar dan saya tidak batuk-batuk. Benar ada sesak napas, tapi tak mesti akibat COVID-19.
Oleh karena itu, disimpulkan bahwa risiko keterpaparan saya terhadap virus COVID-19 amat minim. Saya diperbolehkan pulang dengan membawa obat antibiotik, obat sesak napas, dan obat demam, serta mengantungi nomor telepon hotline Dinas Kesehatan. Apabila dalam 14 hari ke depan kondisi saya memburuk, gejala flu saya kambuh, dan tidak mempan terhadap obat, mereka akan menjemput saya secara langsung untuk dilakukan pemantauan lebih jauh.
Meski sekilas terdengar ganjil, sebetulnya tindakan ini selaras dengan kebijakan pemerintah terkait tes COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Dr. Achmad Yurianto, menyatakan bahwa tak semua orang harus melakukan tes COVID-19. Pemeriksaan COVID-19 diutamakan bagi dua kelompok orang, yakni orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
ODP mengacu pada orang yang baru pulang dari negara yang positif COVID-19, adapun PDP mengacu pada ODP yang mengalami sakit bergejala flu ringan hingga berat, atau orang yang sakit dan diyakini kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. “Kalau dia bukan ODP, bukan PDP, dia tidak memiliki kontak positif yang kuat, ya untuk apa dilakukan tes?” jelas Dr. Yurianto pekan lalu (5/3).
Dr. Yurianto pun menegaskan bahwa tes COVID-19 dilakukan untuk keperluan pemeriksaan saja dan hanya berdasarkan permintaan dokter. Singkatnya, apabila dokter yang memeriksa tak merasa perlu, tes COVID-19 tak akan dilakukan. Selain itu, ia pun menyangkal rumor bahwa tes COVID-19 akan dipungut biaya hingga Rp 750 ribu. “Saya tegaskan lagi tidak ada pungutan serupiah pun dari pemeriksaan COVID,” pungkasnya.
Ada dua hal yang janggal. Pertama, soal prioritas tes COVID-19. Pada mulanya, berbagai negara memang hanya melakukan tes ke orang yang memenuhi kriteria ODP serta PDP. Jika kamu habis pulang dari negara yang kena virus lalu kamu sakit berat, kamu dites.
Namun, analisis terbaru terhadap infeksi di Cina dan Singapura mendapati bahwa orang yang positif COVID-19 dapat menyebarkan virus tersebut meski ia belum menunjukkan gejala sakit. Setelah ditelusuri, pasien ke-27 di Indonesia pun tidak berasal dari luar negeri atau punya sejarah bepergian ke luar negeri.
Ia termasuk kasus local transmission, atau penularan lokal. Maka, menunggu seseorang terlihat sakit sebelum melakukan isolasi diri belum tentu efektif untuk memperlambat persebaran virus. Apalagi menunggu seseorang sakit dan punya sejarah bepergian ke luar negeri, baru mengetesnya untuk COVID-19.
Kedua, pernyataan Dr. Yurianto bahwa tes COVID-19 sepenuhnya gratis memang tepat. Presiden pun telah turun gunung untuk menetapkan bahwa tes tersebut dijamin penuh. Hanya saja, tempo hari saya sekadar diminta tes darah dan rontgen, lalu dokter memutuskan tak perlu dieskalasi ke tes COVID-19. Saya tetap keluar uang lebih dari Rp 500 ribu untuk kedua prosedur tersebut.
Apakah ada orang-orang bernasib sama di luar sana yang tes atas prakarsa sendiri, lalu mendapati keuangannya cekak sampai akhir bulan? Misalkan saya pekerja kerah biru dengan pendapatan tak pasti, atau punya keluarga yang perutnya mesti diprioritaskan, akankah saya mengambil inisiatif serupa? Saya ragu. Boleh jadi tes COVID-19 itu sendiri digratiskan. Tetapi tes-tes lain yang mendahuluinya jelas tidak.
Saat ini juga, saya mengisolir diri di rumah keluarga. Beruntung ada halaman yang asri, lantai agak berdebu, serta kompor, sehingga saya dapat mengamalkan fitrah saya sebagai Cancer: menangani pekerjaan domestik. Banyak pertanyaan yang tersisa setelah kunjungan saya ke rumah sakit.
Apakah protokol penanganan kita sudah tepat sasaran, atau kita lamban beradaptasi? Apakah para pekerja keras di lab Balitbangkes punya waktu dan sumber daya cukup untuk menangani setiap sampel yang masuk? Bila virus ini berkembang dan penularan lokal bertambah, apakah fasilitas kita cukup untuk menampung semua orang? Apakah saya bisa mencuri Wi-Fi tetangga sebelah supaya saya tidak mati berdiri selama 14 hari isolasi?
Entahlah. Di halaman rumah saya banyak rumput bergoyang. Nanti saya tanyakan pada mereka.