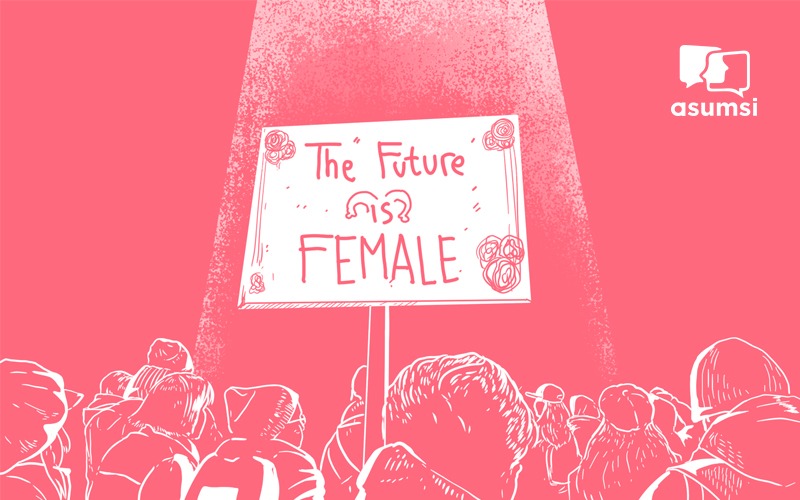Feminisme Bukan Cuma untuk Kelas Menengah Atas
Feminist Festival Indonesia yang hendak berlangsung pada 23-24 November mendatang kena kritik di media sosial. Akun Twitter @mitatweets atau Aria Danaparamita mengkritisi harga tiket festival tersebut yang dipatok relatif mahal, yaitu Rp80.000,00 hingga Rp150.000,00, tergantung jenis tiket. Menurut Mita, sebagai sebuah festival feminis, acara ini seharusnya menjunjung inklusivitas—salah satunya dengan menerapkan sistem tiket yang dapat menjangkau seluruh kalangan.
Panitia telah menyadari bahwa festival ini dapat dibuat lebih inklusif lagi. Pihak-pihak yang tidak mampu dapat mengajukan subsidi agar tetap bisa membeli tiket. Namun, mereka juga menyadari bahwa membuat acaranya sepenuhnya gratis atau bersistem donasi tidak memungkinkan. Sebab, untuk membuat festival berskala nasional, modal yang dibutuhkan pun tidak kecil.
Ada pula permasalahan kelas: pembicara-pembicara dinilai tidak cukup melibatkan kelompok-kelompok marjinal seperti kaum buruh, orang di kawasan Indonesia Timur, dan lain-lain. Namun, inti permasalahannya tetap sama: bagaimana memastikan sebuah acara atau kegiatan bisa menjangkau dan melibatkan seluruh pihak, terutama orang-orang yang dipinggirkan dan minoritas?
Feminisme yang inklusif dan interseksional pun kembali jadi bahan bicaraan. Tentu, hampir semua perempuan rasanya pernah merasakan di-catcall ketika sedang berjalan di tempat umum. Pengalaman ini begitu universal hingga kita bisa sepakat tidak nyamannya dipandang sebagai obyek dan diperlakukan sebagai pemuas hasrat belaka.
Namun, setiap perempuan juga punya pengalaman hidup yang berbeda dari perempuan lain. Tak dimungkiri pula bahwa setiap orang lahir dari latar belakang atau status ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya yang berbeda-beda.
Permasalahan perempuan di negara Barat dan Timur tak akan sepenuhnya serupa. Tak hanya itu, opresi atau diskriminasi yang dialami perempuan kulit putih dan non-kulit putih pun tak bisa disamaratakan. Inilah yang mendasari munculnya gelombang feminisme ketiga.
Feminisme gelombang kedua masih terfokus pada permasalahan dan perjuangan perempuan kulit putih kelas menengah ke atas. Maka, muncullah gelombang feminisme ketiga yang memahami ketidaksetaraan gender sebagai isu yang berkelindan dengan rasisme, homofobia, kelas, dan kolonialisme.
Sementara itu, Indonesia punya ceritanya sendiri. Gerakan-gerakan perempuan digembosi oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Gerwani yang secara progresif menentang domestifikasi perempuan berakhir dihilangkan. Orde Baru juga mendoktrin masyarakat untuk mengenang Gerwani sebagai perkumpulan perempuan yang kerjanya memotong alat kelamin laki-laki.
Feminisme jadi asing di kalangan banyak orang Indonesia saat ini karena, salah satu sebabnya, dihilangkannya jejak-jejak feminisme yang dibawa oleh Gerwani oleh pemerintah. “Di Barat itu feminisme bisa ada gelombang satu, dua, tiga, itu kan karena korpus-korpus pemikiran perempuan ini ada. Kalau di Indonesia ada teks dan ada kajiannya (tentang Gerwani dan perjuangannya) kita bisa tahu gimana gelombang feminisme di Indonesia,” kata Dewi Kharisma Michellia, penulis dan salah satu pendiri Ruang Perempuan dan Tulisan.
Begitu pula dengan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Hari ini awalnya diperingatkan sebagai Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Namun, saat ini, Hari Ibu diperingati sekadar untuk mengingat peran perempuan yang telah punya anak.
Diskriminasi dan kekerasan gender ini tak berhenti pada Orde Baru. Saat ini, perempuan Indonesia masih rentan mengalami seksisme, pelecehan, dan kekerasan seksual. Perempuan kelas menengah yang punya pekerjaan tetap bisa mengalami pelecehan seksual dari atasannya, atau sekadar digaji lebih rendah dari rekan kerja laki-lakinya yang punya posisi setara.
Keresahan-keresahan ini bisa dengan mudah dibagikan dengan kemudahan akses internet, alat komunikasi, dan alat transportasi lain di perkotaan. Maka, bagaimana ceritanya bagi mereka yang tak punya cukup akses akan itu dan tidak bisa membagikan ceritanya?
Lihatlah transgender di Aceh yang rumahnya digrebek, ditangkap oleh aparat, ditelanjangi, hingga memangkas paksa rambut mereka. Lingkungan masyarakat yang opresif ini pun membuat lapangan pekerjaan untuk mereka terbatasi.
Kekerasan juga dialami oleh para buruh garmen. Para perempuan mengalami pelecehan seksual ketika bekerja, mesti bekerja lembur tanpa upah yang layak—bahkan seringkali tidak dibayar, hingga kondisi toilet yang kotor dan bau.
Ada pula masalah-masalah perempuan adat yang begitu pelik. Devi Anggraini selaku Ketua Umum Perempuan AMAN mengatakan bahwa pembukaan lahan sawit di Kalimantan dan Sumatera membuat perempuan paling kena ruginya. Perempuan adat tak punya hak milik atas tanah, sumber daya di sekitar tempat tinggal mereka telah tercemar, hingga pelecehan seksual yang dialami oleh buruh-buruh perempuan adat di lahan sawit.
“Mau menanam untuk kebutuhan hidup sendiri nggak bisa. Dulu, cabe mereka bisa tanam sendiri, sekarang harus beli. Sumber mata air kering. Mereka harus bekerja di perusahaan. Nggak dikasih layanan pendidikan buat anak-anak nggak ada. Tempat ibadah nggak punya,” kata Devi.
Inilah yang mendasari konsep feminisme interseksional. Selain gender, seseorang lahir dengan ras, seksualitas, kelas, kemampuan fisik dan mental yang berbeda. Untuk benar-benar merayakan feminisme yang inklusif, penting bagi feminis untuk menyadari dan membahas jenis-jenis opresi yang dialami oleh kelompok terpinggirkan.
Lailatul Fitriyah, seorang feminis dan teolog muslim Departemen Teologi Universitas Notre Dame, mengatakan pentingnya menerapkan feminis yang inklusif dan interseksional. “Dalam feminisme interseksional, mereka yang punya privilese harus refleksi lebih banyak. Bukan hanya menjadi sekutu bagi mereka yang marjinal, tapi harus terlibat dalam praktik transfer kuasa kepada mereka,” kata Laily.
Tak dimungkiri bahwa setiap perempuan menderita di bawah patriarki. Tetapi, penting pula untuk menyadari privilese yang mungkin tak dimiliki oleh sebagian perempuan lainnya. “Dari setiap privilese yang kita miliki, ada kelompok-kelompok orang yang haknya untuk menikmati privilese tersebut tercerabut. Privilese kita adalah opresi bagi orang lain,” lanjut Laily.
Untuk itu, orang-orang yang punya sumber daya atau punya privilese lebih seharusnya bisa turut memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk bicara. ”Ketika masuk bahasan tentang kehidupan perempuan marjinal, kita (yang memiliki privilese) harus berhenti menyuarakan opresi yang kita miliki. Berikan ruang untuk mereka (para perempuan yang terpinggirkan) sepenuhnya,” tandasnya.